Surat ini ditulis oleh putri saya setahun lalu.
Tadinya mau buat lomba, tapi begitu naskah dikirim, penyelenggaranya menghilang.
Ketika saya beres-beres file, muncullah surat ini.
Saya post di sini saja 🙂
Bandung, 2 April 2020
Assalaamualaikum,
Pak Nadiem, apa kabar?
Semoga Bapak selalu sehat, amin.
Nama saya Qosima, kelas VII SMPN 37 Bandung. Sekolah saya di dekat rumah, jadi saya jalan kaki pulang pergi. Bersama teman-teman, saya biasa lewat gang-gang kecil. Lebih aman daripada lewat jalan besar tapi sering macet. Tikungannya seram, sering membuat saya kaget karena mendadak ada kendaraan dari depan.
Buat saya, berangkat dan pulang sekolah bersama-sama itu seru, apalagi kalau musim hujan. Di tas saya selalu ada sandal jepit dan payung. Jadi begitu hujan turun, saya dan teman-teman lepas sepatu, lalu menerobos jalan dan gang-gang yang penuh genangan air.
Kalau hujan deras dan lama, jalan menuju rumah pasti banjir. Saya cemas tapi senang juga, soalnya bisa main air di jalan sambil bercerita dengan teman-teman. Saya tahu airnya kotor, kan luapan dari selokan. Tapi saya bisa cuci kaki di rumah.
Kalau hari panas, saya dan teman-teman berjalan berputar-putar dulu supaya punya lebih banyak waktu bercerita. Walau sudah seharian bersama di sekolah, berjalan bersama sepulang sekolah itu menyenangkan.
Tiba-tiba kesenangan itu hilang. Karena corona, kami harus belajar di rumah.
Serius, Pak Nadiem.
Dua minggu belajar di rumah itu sudah lama sekali. Eh, setelah itu, ternyata diperpanjang dua minggu lagi. Sejak mulai belajar di rumah, saya tidak pernah menginjak aspal jalanan. Keluar rumah untuk membeli camilan pun tidak. Membosankan sekali.
Selain bosan, tugas juga menumpuk. Dalam sehari, kami bisa dapat enam tugas dari mata pelajaran yang berbeda! Biarpun waktunya masih banyak, entah mengapa saya merasa sedikit terbebani. Mengerjakan satu soal saja tidak bisa fokus karena memikirkan tugas-tugas lainnya.
Sudah pasti bukan hanya saya yang pusing. Teman-teman sekelas saya juga ribut saling bertanya. Grup di hape yang biasanya sepi sekarang selalu berbunyi, penuh dengan pertanyaan. Tentu saja grup kelas tidak hanya satu, karena pelajarannya kan banyak. Hape saya yang lelet terus bergetar dan berdering.
Guru-guru saya juga meminta muridnya difoto ketika sedang mengerjakan tugas sebagai bukti. Ada yang minta kami membuat video juga. Tujuannya biar kami benar-benar belajar. Tapi kadang itu merepotkan. Yah, memang hari-hari pertama belajar di rumah sangat berantakan. Belum lagi kegiatan lainnya.
Selain sekolah, saya juga menekuni olahraga wushu, khususnya taiji. Biasanya saya latihan di sasana empat kali seminggu.
Karena sedang ada wabah, latihannya juga jadi di rumah, deh. Saya latihan di tempat jemuran. Ibu saya selalu menyuruh saya dan kakak-kakak berjemur. Di tempat jemuran itu saya harus pakai sepatu karena banyak batu dan kerikil. Lantainya juga tidak rata, ditambah ada tiang dan tali jemuran. Jadi susah sekali bergerak dengan benar.
Setiap pagi saya latihan sambil ditemani Ibu. Saya skipping, latihan fisik, latihan kuda-kuda, dan latihan jurus. Ibu ikut berjemur, kadang sambil menjemur baju. Kadang kakak-kakak saya juga ikutan biar saya semangat. Tapi tetap saja, latihan di rumah itu aneh rasanya.
Dipikir-pikir, jadwal di sasana kan empat kali seminggu, sekarang saya jadi latihan setiap hari. Baru sebentar, keringat saya mengucur terus. Bukan hanya karena capek, tapi juga karena berjemur di bawah sinar matahari yang begitu terik!
Pak Nadiem,
Beneran. Latihan sendirian itu tidak menyenangkan. Saya dan teman-teman biasa latihan dua jam tanpa henti di sasana dan tetap senang. Kalau sendiri, 30 menit saja saya sudah capek, tidak mood, lalu cari gara-gara biar bisa istirahat atau berhenti. Ambil minum, lah. Ke kamar mandi, lah. Sepatu kemasukan kerikil, lah. Atau cek hape siapa tahu ada tugas. Kalau sudah begitu, Ibu pasti mengomel.
Tapi, yang paling membuat saya heran adalah banyak anak yang masih saja bermain di luar. Entah siapa mereka, saya tidak kenal. Mereka main bareng-bareng, bersepeda, bahkan naik sepeda motor hingga malam tiba. Seperti sedang liburan!
Beberapa teman sekolah saya juga bilang biasa saja keluar rumah, santai saja dengan larangan tidak boleh keluar rumah sembarangan. Padahal ada risiko tertular dan ikut menyebarkan wabahnya. Beberapa teman lain mengingatkan, lalu jadi bertengkar di grup.
Pak Nadiem,
Saya bosan sekali di rumah terus.
Saya ingin segera kembali ke sekolah bertemu lagi dengan teman-teman. Saya juga ingin ke sasana. Saya rindu matrasnya. Di rumah, saya tidak berani lompat karena takut cedera. Saya juga rindu pergi latihan diantar Ibu, lalu singgah beli susu murni di pinggir jalan.
Itu saja cerita saya, Pak. Maaf jadi curhat macam-macam. Saya sekarang berusaha senang dan tidak bete lagi. Kan rugi, saya marah-marah juga tetap tidak bisa keluar. Saya berdoa berharap semua ini cepat selesai dan bisa keluar rumah lagi tanpa rasa was-was.
Terima kasih atas waktu Bapak membaca surat ini.
Wassalamualaikum,
Qosima Luthfa Anvari.







 Untuk satu buku, saya membuat dua resensi. Yang satu dimuat di Harian Umum Pikiran Rakyat, satu lagi di Majalah Pendidikan Jawa Barat, Suara Daerah, edisi 525 tahun 2017.
Untuk satu buku, saya membuat dua resensi. Yang satu dimuat di Harian Umum Pikiran Rakyat, satu lagi di Majalah Pendidikan Jawa Barat, Suara Daerah, edisi 525 tahun 2017.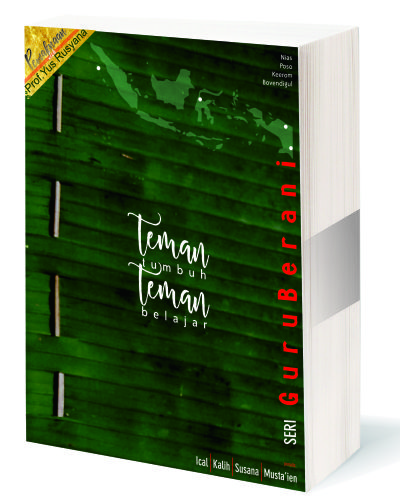

 For me, opinion is merely curhat with style 😀
For me, opinion is merely curhat with style 😀 Opini ini dimuat di Harian Galamedia, 22 Desember 2016. Seperti biasa, tulisan saya di koran lebih padat, berisi, rapi. Terima kasih kepada editornya yang jeli menatanya.
Opini ini dimuat di Harian Galamedia, 22 Desember 2016. Seperti biasa, tulisan saya di koran lebih padat, berisi, rapi. Terima kasih kepada editornya yang jeli menatanya.